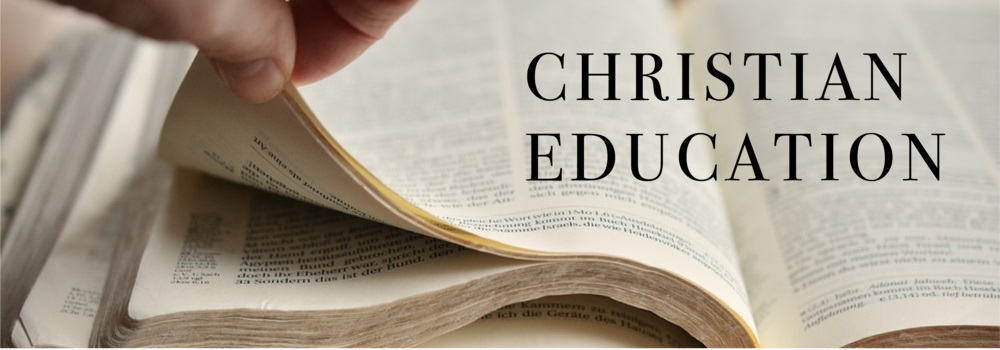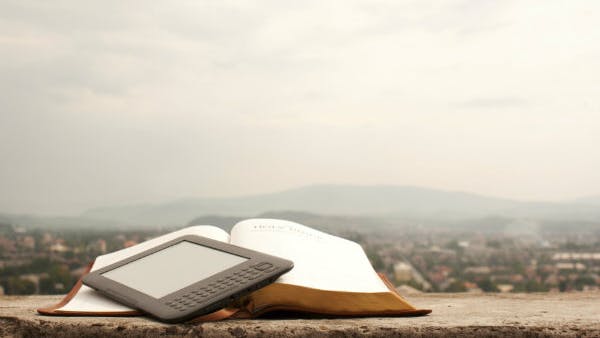Sumber-sumber apa saja yang sudah Anda miliki untuk mengakses informasi mengenai tokoh-tokoh Alkitab maupun tokoh-tokoh Kristen di dunia? Apakah salah satunya adalah Publikasi Bio-Kristi?
Dear e-Reformed Netters,
Sehubungan dengan hari Reformasi Gereja, yang akan diperingati tanggal 31 Oktober nanti, maka secara khusus edisi e-Reformed akan menyuguhkan sebuah artikel yang sedikit mengulik kehidupan sosial seorang tokoh besar reformasi, yaitu John Calvin. Di balik pribadinya yang begitu serius dan mungkin terkesan sangat kaku dalam prinsip-prinsip pemikiran Kristen, ternyata John Calvin memiliki sisi lain yang unik yang banyak tidak diketahui orang. Karena kesan sifat kakunya itu, banyak orang berpikir bahwa John Calvin tidak memiliki banyak rekan dan sahabat. Ternyata, pandangan itu salah besar. Jika kita mengenal John Calvin lebih dekat, sebagaimana dialami oleh rekan-rekan dekat John Calvin, kita akan mendapati dia ternyata seorang pribadi yang hangat, setia, dan sangat perhatian. Melalui artikel yang kami sajikan di bawah ini, kita akan lebih mengenal John Calvin, tidak hanya dalam intelektualitas teologinya, tetapi juga dalam hal berelasi dengan orang lain. Kiranya kita juga bisa belajar dari pribadi John Calvin yang tidak hanya serius dalam mengerjakan panggilannya, tetapi juga menjadi pribadi yang hangat dan setia pada sahabat-sahabatnya. Selamat membaca. Soli Deo Gloria.
Pemimpin Redaksi e-Reformed,
Ayub
< ayub(at)in-christ.net >
< http://reformed.sabda.org >
Persahabatan-Persahabatan Calvin
Seorang pembela Calvin mengatakan bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang menjadi sangat dikasihi pada saat kematiannya apabila pada waktu hidupnya ia adalah seorang yang jahat. Bukan saja Calvin dipuji pada saat kematiannya, tetapi banyak temannya memiliki gagasan-gagasan yang sama dan terus melanjutkan usahanya.
Sebuah studi mengenai surat-surat Calvin menyingkapkan suatu pola persahabatan dan perekanan. Tentu saja Calvin tidak memandang dirinya sebagai satu-satunya individu yang terlibat dalam masalah-masalah reformasi ini. Satu studi semacam itu adalah The Humanness of John Calvin oleh Richard Stauffer. Untuk "sisi lain dari kisah itu", kita perlu melihat karya pendek ini. Dalam kata pembukaan kepada monograf itu, sarjana Calvin yang terkemuka, J.T. McNeill, mengkronologikan bagaimana ia sampai mempertanyakan "desas-desus" tentang Calvin. Ketika McNeill membaca surat-surat Calvin, berlawanan dengan banyak legenda urban yang telah ia dengar, ia menemukan bahwa Calvin itu jelas-jelas peramah, berkawan dengan orang kaya maupun orang miskin, dan menunjukkan kesetiaan yang kokoh kepada teman-temannya. McNeill menemukan bahwa Calvin sesungguhnya lemah lembut, hangat, murah hati, dan ramah. Richard Stauffer mendokumentasikan "fitnah" yang telah Calvin terima dari musuh-musuhnya dan juga bagaimana ia telah "disalahpahami dan disalahtafsirkan oleh buyut-buyutnya".
Sejarawan lain mencatat bahwa tidak ada Reformator lain yang melebihi Calvin dalam menunjukkan kesetiaan pribadi. Emile Doumergue berkata demikian, "Hanya segelintir orang saja yang dapat memiliki banyak sahabat seperti Calvin dan yang tahu bagaimana mempertahankan bukan hanya rasa kagum, tetapi juga afeksi pribadi dari teman-temannya." Abel Lefranc mengekspresikan perasaan yang sama demikian: "Persahabatan yang ia inspirasikan dengan guru-gurunya maupun rekan-rekannya, merupakan kesaksian-kesaksian yang cukup kuat bagi fakta bahwa ia tahu bagaimana menggabungkan komitmennya yang sungguh-sungguh dan mendalam terhadap pekerjaan dengan keramahtamahan dan keluwesan yang mampu mengambil hati setiap orang terhadapnya."
Entah ia berada di lingkungan universitas atau mengambil pengalaman dari guru-gurunya untuk membantu dia, Calvin, tidak seperti dugaan tentang dirinya, lebih merupakan orang yang suka bergaul. Ia terbiasa menulis surat, berkoresponden dengan ahli-ahli hukum, gubernur-gubernur, orang kebanyakan, dan banyak hamba Tuhan. Surat-surat ini memberikan pandangan-pandangan sekilas ke dalam diri Calvin yang sesungguhnya. Dalam surat-surat ini, ia dapat menunjukkan afeksi yang ia miliki terhadap gurunya, Melchior Wolmar, dan pada waktu yang sama dapat meratapi meninggalnya seorang teman sepelayanan yang begitu mengejutkan sehingga membuatnya berdukacita.
Karakter dan denyut Calvinisme memengaruhi dunia melalui suatu persaudaraan dari teman-temannya yang setia dan berkomitmen. Teolog Amerika, Douglas Kelly, menegaskan bahwa tradisi Calvinistik mempunyai pengaruh jauh melampaui Swiss dan Prancis. Barangkali warisan yang paling abadi dari tradisi ini adalah penekanannya pada kedaulatan rakyat dan hak untuk melawan tirani, suatu ajaran yang "akan diteruskan (baik secara tidak langsung dan digabung dengan ide-ide dari sumber lainnya) ke dalam teori-teori politik di Inggris pada akhir abad ketujuh belas mengenai hak-hak asasi manusia ... [dan] debat-debat serupa di bidang hukum dan pemerintahan di Amerika pada abad kedelapan belas". Satu orang saja tidak dapat menabur begitu banyak benih; kemenangan-kemenangan ini didapat oleh suatu tim rekan-rekan.
Calvin adalah teoretikus Protestan yang utama, tetapi tentu saja bukan satu-satunya. Reformator-reformator lain yang ada dalam lingkungan persahabatannya mengartikulasikan secara tajam karya-karya politik yang sesungguhnya merupakan teologi-teologi tentang negara, dengan karya-karya seminar berikut yang muncul berturut-turut dengan cepatnya dalam waktu kurang dari tiga puluh tahun: buku Martin Bucer De Regno Christi (1551), buku John Ponet A Short Treatise of Political Power (1556), buku How Superior Powers Ought to Be Obeyed By Their Subjects: and Where in They May Lawfully By God's Word Be Disobeyed And Resisted (1558), buku Peter Viret The World and the Empire (1561), buku Francois Hotman Francogaltia (1573), buku Theodore Beza De Jure Magisterium (1574), buku ,George Buchanan De Jure Regni Apud Scotos (1579), dan buku Languet Vindiciae Contra Tyrannos (1579). Masing-masing karya ini melegitimasi gagasan tentang penolakan warga negara terhadap perluasan pemerintahan yang melampaui batas-batas semestinya. Menariknya, bagian terbesar dari pemikiran politis ini berasal dari lingkaran teman-teman yang erat, yang kebanyakan mempunyai kontak dengan Calvin. Sulit untuk mengatakan bahwa kesamaan pikiran yang sedemikian kokoh ini hanyalah kebetulan.
Persahabatan Calvin dengan Theodore Beza merupakan sebuah teladan dalam persahabatan. Di tengah-tengah semua masalah intelektual yang memusingkan kepala pada zaman itu dan tantangan-tantangan yang menyertainya, apa yang paling berkesan bagi Beza adalah dukungan pribadi dan persahabatan Calvin. Jadi, Beza (dan yang lain) menulis tentang persahabatan yang Calvin berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Calvin merupakan contoh gagasan modern tentang perekanan, dan ia cukup bijaksana untuk menarik teman-teman yang brilian jika memungkinkan. Pernah, ketika Beza sakit, Calvin mengakui ketakutannya sendiri dan kesedihannya yang dalam setelah mengetahui penyakit rekannya. Ia menangis dan berduka, tampaknya karena terkejut akan kehilangan yang mungkin sekali terjadi pada gereja dan padanya secara pribadi. Untungnya, Beza sembuh.
Ada banyak teman yang lain di samping Beza. Jenis pemikiran yang sama yang mengalir melalui nadi-nadi literatur Bullinger, Bucer, Viret, dan Calvin -- segera ditambah oleh Knox, Beza, Hotman, dan Junius Brutus -- membentuk suatu tradisi intelektual dengan Jenewa sebagai episenternya dan Calvin sebagai bapaknya. Persahabatannya dengan para cendekiawan ini ternyata merupakan petunjuk yang menyatukan gerakan itu dalam masa pertumbuhannya yang sulit. J. H. Merle D'Aubigne mencatat saling menukar gagasan-gagasan ini dalam kata-kata berikut:
"Kekatolikan Reformasi merupakan ciri yang mulia dalam karakternya. Orang-orang Jerman masuk ke Swiss; orang Prancis ke Jerman; dalam waktu-waktu belakangan orang-orang dari Inggris dan Skotlandia pergi ke Eropa Daratan, dan doktor-doktor dari Eropa Daratan ke Inggris Raya. Reformator-reformator di negara-negara yang berbeda bermunculan hampir tanpa ada kaitannya satu sama lain, tetapi begitu muncul, mereka mengulurkan tangan persekutuan .... Merupakan suatu kesalahan, dalam pendapat kami, jika menulis sebagaimana yang masih terjadi sampai sekarang, tentang sejarah Reformasi untuk satu negeri karena Reformasi itu satu.
Teman-teman Calvin berfungsi untuk menstabilkan dan menstandarisasi suatu gerakan internasional.
Calvin, Farel, dan Peter Viret disebut "tripod" atau "tiga bapak", karena begitu terkenalnya persahabatan mereka. Dalam "Commentary on Titus", Calvin menulis bahwa ia "tidak percaya kalau pernah ada teman-teman seperti itu yang hidup bersama-sama dalam persahabatan yang sedemikian erat dalam gaya hidup mereka sehari-hari di dunia ini seperti yang kami miliki dalam pelayanan kami". Bahkan, ketika ada ketidaksetujuan yang kuat, Calvin merupakan suatu paradigma persahabatan. Ketika Reformator-reformator ini mengalami pergumulan-pergumulan atau sukacita keluarga, Calvin menceritakannya dalam surat-suratnya. Surat-surat kepada berbagai Reformator ini penuh dengan simpati dan cepat menggambarkan kesetiaan yang sehat. Terlebih lagi, korespondensinya dengan pengungsi-pengungsi menunjukkan belas kasihnya yang besar. Bahkan, ia membangun jembatan-jembatan dengan murid-murid Luther setelah pemimpin Jerman itu mencelanya. Calvin menerjemahkan sebuah karya teologis Melanchthon, murid Luther yang terutama.
Apa yang dimulai di Jenewa dengan kader rekan-rekan multinasional, yang semuanya berusaha meluaskan "republik Kristus" bertumbuh menjadi suatu gerakan yang bercirikan teologi, gagasan-gagasan, dan pandangan unik tentang sejarah yang menyebar jauh melampaui kota Jenewa. Dengan keyakinan mereka kepada providensi Allah dan pemilihan ilahi, lingkaran teman-teman ini mendorong pemimpin-pemimpin sipil untuk mengadopsi pandangan-pandangan religius dan praktik-praktik politik mereka "yang menyatakan bahwa tidak ada perbatasan-perbatasan, batas-batas, kekang-kekang yang boleh membatasi semangat pangeran-pangeran yang saleh dalam hal kemuliaan Allah dan pemerintahan Kristus". Bagi sejumlah pihak, teologi mereka tentang perlawanan secara politik tampak subversif.
Kadang-kadang, sebagaimana dalam era mana pun, juga ada gangguan-gangguan persahabatan. Calvin harus membantu anggota-anggota gereja dalam hal hubungan-hubungan yang retak, dan ia harus menangani friksi di antara reformator-reformator Protestan. Tidak seorang pemimpin pun seharusnya mengharapkan bahwa segala sesuatu akan selalu berjalan lancar dalam bidang persahabatan. Meskipun demikian, Calvin belajar mendorong orang-orang di sekitarnya dan ia mendelegasikan beberapa tanggung jawab kepada teman-teman sejawatnya.
Richard Stauffer menyimpulkan bahwa Calvin jauh dari "pahlawan yang terisolasi atau jenius yang kesepian yang sering digambarkan tentang dirinya. Sepanjang kariernya, ia memiliki hubungan-hubungan dengan teman-teman yang menunjukkan afeksinya yang tidak ada habis-habisnya dan pengabdian yang tidak kenal lelah. Jika ia menunjukkan pesona seperti itu, hal itu pasti karena ia sendiri merupakan seorang teman yang tidak ada bandingannya. Untuk pengabdian yang orang tunjukkan kepadanya, ia membalas dengan kesetiaan yang tidak tergoyahkan." Setelah kematian Calvin, menjadi tugas rekan-rekannya yang ditunjukkan oleh patung Beza dalam pahatan terkenal pada dinding Reformasi di Jenewa -- untuk menyebarkan firman.
Persahabatan-Persahabatan Calvin
| Diambil dari: | ||
| Judul buku | : | Legacy of John Calvin: His Influence on the Modern World |
| Judul buku terjemahan | : | Warisan John Calvin: Pengaruhnya di Dunia Modern |
| Judul bab | : | John Calvin: Suatu Kehidupan yang Patut Diketahui |
| Judul asli artikel | : | Persahabatan-persahabatan Calvin |
| Penulis artikel | : | David W. Hall |
| Penerjemah | : | Lanna Wahyuni |
| Penerbit | : | Momentum, Surabaya 2010 |
| Halaman | : | 69 -- 76 |
Dear e-Reformed Netters,
Artikel ini adalah lanjutan dari artikel edisi sebelumnya. Setelah kita memahami latar belakang munculnya teologi feminisme, dalam artikel ini kita akan mempelajari dasar dan pandangan Alkitab yang dikutip oleh para teolog feminisme dalam mendukung gerakan feminisme serta evaluasi terhadap teologi feminisme. Kiranya sajian kami menjadi berkat bagi kita sekalian. Soli Deo Gloria.
Pemimpin Redaksi e-Reformed,
Ayub
< ayub(at)in-christ.net >
http://reformed.sabda.org
Metode Teologi
".....otoritas Alkitab menurut Russell adalah otoritas yang pragmatis, tidak penting apakah Alkitab bisa salah atau tidak, yang penting baginya adalah Alkitab itu memiliki kebergunaan dalam kehidupannya."
Dengan pandangan yang cukup negatif tentang Alkitab seperti yang di uraikan di atas, timbul pertanyaan: berita positif apa yang terdapat dalam Alkitab bagi para feminis? Menurut Russell, Alkitab adalah firman yang memerdekakan (liberating word). Hal ini jelas terlihat sejak peristiwa eksodus yang dicatat dalam Alkitab sampai zaman para nabi dan kemudian jauh hingga zaman Tuhan Yesus. Peristiwa eksodus yang dicatat dalam kitab jelas memperlihatkan karya pembebasan Allah bagi Israel dari penindasan Mesir. Nubuat yang disampaikan para nabi pun berbicara tentang pembebasan dari penindasan, seperti yang dicatat dalam Yesaya 61:1-2. Teks ini pulalah yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 4:18 yang dilanjutkan dengan pernyataan Tuhan Yesus pada ayat 21, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya."
Selanjutnya, dengan sedikit permainan kata Russell mengatakan bahwa Alkitab bukan saja merupakan the liberating word tetapi juga harus menjadi "liberated word" (firman yang merdeka). Apa yang ia maksud dengan "the liberated word"? The liberated word berarti Alkitab dibebaskan dari cara pandang patriarkhal. Caranya adalah dengan membuang semua budaya patriarkhal yang telah membelenggu teks-teks Alkitab, untuk menemukan berita pembebasan kaum wanita.
Senada dengan pandangan di atas, menurut Ruether Alkitab harus dilihat sebagai tradisi profetik-mesianis, yakni melihat Alkitab dari perspektif kritis, ketika tradisi biblikal harus terus-menerus dievaluasi ulang dalam teks yang baru. Yang ia maksud dengan evaluasi ulang adalah melihat dan menilai Alkitab dengan paradigma pembebasan, dan konteksnya tidak lain adalah pengalaman kaum wanita. Sedangkan yang dimaksud tradisi profetik-mesianik adalah sebagaimana para nabi memberitakan penghakiman Allah, demikian juga para feminis memberitakan penghakiman atas ketidakadilan yang selama ini telah berlangsung, serta menuntut pertobatan dan adanya perubahan. Kaum feminis tidak hanya dipanggil untuk memberitakan berita penghakiman (profetik), tetapi ada juga unsur mesianisnya, artinya ada kabar "keselamatan" bagi kaum wanita, yakni pembebasan dari ketidakadilan. Masih menurut Ruether, tradisi profetik-mesianik ini menjadi ukuran atau norma untuk menilai teks-teks Alkitab yang lain."
Para feminis juga berpendapat bahwa teologi harus merupakan gabungan antara pertanyaan budaya kontemporer dan jawabannya, yang jawaban tersebut ditentukan oleh latar belakang budaya kontemporer (budaya pada waktu pertanyaan tersebut dilontarkan). Pada masa kini, situasi budaya ke mana tradisi Kristen itu harus dihubungkan adalah bertumbuhnya kesadaran wanita atau pengalaman kaum wanita di gereja. Oleh karena itu, pengalaman kaum wanita harus menjadi sumber dan norma bagi teologi Kristen kontemporer yang serius. Pendeknya, menurut Ruether, pengalaman manusia harus menjadi starting point dan ending point dalam berteologi.
Dasar Alkitab
Bagian Alkitab yang paling sering dikutip oleh teolog-teolog feminis dan diklaim sebagai dasar teologi mereka, yang juga dikenal sebagai magna carta of humanity adalah Galatia 3:28 yang berbunyi: "Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di alam Kristus Yesus." Galatia 3:28 dipandang sebagai ayat yang membebaskan wanita dari penindasan, dominasi, dan subordinasi pria. Bagian-bagian lain yang juga berbicara tentang kesederajatan adalah Kejadian 34:12; Keluaran 21:7; 22:17; Imamat 12:1-5; Ulangan 24:1-4; 1 Samuel 18:25 yang berbicara bahwa wanita dan pria memiliki status sosial yang sama; Hakim-hakim 4:4; 5:28-29; 2 Samuel 14:2; 20:16; 2 Raja-raja 1:3; 22:14; Nehemia 6:14 adalah ayat-ayat yang memperlihatkan bahwa wanita memiliki tempat dalam kehidupan religius dan sosial bangsa Israel, kecuali dalam hal keimaman; sedangkan dalam Kejadian 1:27 dikatakan bahwa wanita dan pria adalah makhluk yang sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat di atas khususnya Galatia 3:28, para feminis menyimpulkan bahwa Paulus dengan jelas mengukuhkan kesetaraan antara pria dan wanita dalam komunitas Kristen; pria dan wanita memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama baik di gereja maupun dalam rumah tangga. Kesimpulan lain dari penafsiran ini ialah bahwa tujuan panggilan Kristen adalah kemerdekaan.
Selain itu, di dalam usaha menelaah sejarah kaum wanita di dalam Alkitab, teolog-teolog feminis tidak hanya menemukan ide tentang kesederajatan pria dan wanita. Di dalam Alkitab mereka juga menemukan bahwa Allah orang Kristen bukan Allah yang paternal; dari sejumlah ayat yang terdapat di Alkitab mereka menemukan bukti-bukti yang mendukung konsep Allah yang maternal. Itulah sebabnya, sebagian teolog feminis menuntut agar Allah tidak hanya disebut sebagai Bapa tetapi juga Ibu. Secara tajam mereka pun mengkritik rumusan baptisan yang berbunyi: dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus."
Kesimpulan
Dari pandangan mereka terhadap Alkitab secara ringkas dapat dikatakan bahwa bagi para feminis, esensi kekristenan adalah panggilan kenabian serta pembebasan bagi kaum tertindas. Atas dasar inilah para feminis menuntut adanya suatu pembaharuan dalam teologi. Menurut mereka, hingga awal abad ke-19 karya-karya teologis dan intelektual kebanyakan dihasilkan dari perspektif nonfeminis; dunia teologi dan intelektual pada masa itu adalah dunia kaum lelaki. Sudah tiba saatnya pengalaman kaum wanita menjadi pusat refleksi teologis dan menjadi kunci menuju hermeneutik atau teori interpretasi.
Evaluasi
Teologi feminis telah memberikan kontribusi yang sangat besar baik bagi gereja dan juga terutama bagi kaum wanita. Namun, di samping sumbangsih yang diberikannya, tidak dapat dimungkiri bahwa teologi ini juga problematik. Dalam bagian ini saya mencoba untuk mengevaluasi teologi feminis baik secara negatif maupun positif.
Salah satu hal penting dalam berteologi adalah sumber teologi itu sendiri. Teolog-teolog feminis beranggapan bahwa teologi mereka bersumber atau berdasar pada Alkitab, firman Allah yang diinspirasikan. Namun, ternyata yang dimaksud dengan diinspirasikan Allah menurut mereka tidak sama dengan yang diyakini oleh iman tradisional. Inspirasi menurut iman Kristen tradisional berarti pimpinan Roh Allah secara supernatural dalam pikiran para penulis Alkitab yang menjamin ineransi, infalibilitas, dan otoritasnya. Akan tetapi, inspirasi menurut feminis tidaklah demikian. Yang dimaksud dengan inspirasi adalah bahwa Allah menyampaikan firman-Nya di dalam dan melalui kata-kata manusia yang bisa saja salah. Bagi para feminis, inspirasi tidak menjamin otoritas dan ineransi Alkitab. Alkitab bisa saja salah, berkontradiksi, dan tidak konsisten karena adanya unsur keterbatasan manusia. Dengan demikian, bagi para feminis Alkitab tidak lebih dari "sumber" yang otoritasnya ditentukan oleh pembacanya, dalam hal ini adalah wanita. Alkitab bukan sumber yang normatif dan berotoritas karena yang menjadi norma adalah pengalaman dan perjuangan kaum wanita untuk mencapai kemerdekaan.
Pandangan demikian jelas tidak benar. Jika kita mendapat Alkitab yang falibel (yang dapat keliru - Red.) dari manusia yang juga falibel, lalu bagaimana kita menentukan mana yang benar dan mana yang salah? Yang cukup menggelikan adalah bagaimana mungkin teolog-teolog feminis menolak otoritas Alkitab, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga menggunakan Alkitab yang berotoritas sebagai dasar teologi mereka? Tolbert melihat hal ini sebagai sebuah paradoks: "So, one must struggle against God as enemy assisted by God as helper, or one must defeat the Bible as patriarchal authority by using the Bible as liberator. Feminist hermeneutics, then, is profoundly paradoxical." ("Jadi, seseorang harus berjuang melawan Allah sebagai musuh, yang dibantu oleh Allah sebagai penolong, atau seseorang harus mengalahkan Alkitab sebagai otoritas patriarkhal dengan menggunakan Alkitab sebagai pembebas. Jika demikian, hermeneutika feminis benar-benar paradoks." - Red.)
Masalah lain dengan teologi feminis adalah metode penghilangan budaya (dekulturisasi) mereka, yang sedikit banyak tidak jauh berbeda dengan metode demitologisasi Bultmann. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa bagian-bagian Alkitab tertentu dikondisikan oleh budaya pada saat itu dan oleh karenanya tidak berotoritas? Bagian-bagian mana yang masih relevan hingga kini? Pertanyaan lebih lanjut, siapa yang berhak menentukan bagian mana yang terkondisi atau terpengaruh oleh budaya dan mana yang tidak? Atau, siapa yang dapat menjamin bahwa proses ini, dekulturisasi (dan juga demitologisasi) tidak akan menghapus berita esensial Alkitab?
Teologi feminis berpijak bukan pada firman Allah melainkan pada pengalaman kaum wanita yang tertindas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teologi ini bersifat eksistensialis karena lebih berpusat pada diri manusia daripada Allah. Teologi ini juga bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh kepentingan dan keprihatinan terhadap wanita yang akhirnya mendistorsi berita itu sendiri. Seperti halnya teologi pembebasan yang dicetuskan Gustavo Gutierrez, injil sosialnya Walter Rauschenbusch, ataupun "black theology"-nya James Cone, teologi feminis dapat dikategorikan sebagai teologi protes. Dalam teologi "protestan," baik melawan ketidakadilan, kesenjangan sosial, gender, ataupun ras diskriminasi, akan ada bahaya bila seluruh energi serta perhatian kita dicurahkan hanya pada isu-isu yang dikemukakan dan lepas dari pusat teologi Kristen, yaitu karya Allah di dalam dan melalui Kristus. Berkaitan dengan feminis, bahaya yang ada misalnya, jika kita tidak lagi mengakui iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan karena Ia adalah laki-laki dan laki-laki identik dengan musuh.
Seperti mata uang, teologi feminis juga memiliki dua sisi. Di samping yang negatif ada juga hal-hal positif yang dapat kita petik dari teologi ini. Memang tidak dapat disangkal bahwa penindasan terhadap wanita sudah berlangsung begitu lama dan melukai banyak wanita. Usaha para teolog feminis untuk kembali meneliti Alkitab memberikan sumbangsih yang sangat besar. Lepas dari subjektivitas penafsiran mereka, kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia (baik pria maupun wanita), memiliki derajat yang sama sebagai gambar dan rupa-Nya. Dosa telah merusak keduanya, bukan hanya Hawa. Walaupun Paulus dalam 1 Timotius 2:14 berkata, "bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa," tidak berarti bahwa Adam bebas dari tanggung jawab. Teolog yang antifeminis mengutip ayat ini dan mengecam teologi feminis, tetapi mengabaikan perkataan Paulus dalam Roma 5 yang mengatakan bahwa dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dari sini kita melihat bahwa acap kali kita memberi kritikan dan kecaman, tetapi pada dasarnya kita juga tidak fair (adil) dan jatuh pada kesalahan yang sama dengan teologi feminis yakni mengambil satu bagian Alkitab dan mengabaikan yang lain, hanya untuk mendukung argumentasi atau melegitimasi tindakan kita.
Teologi feminis dimulai dari situasi penindasan terhadap wanita baik di dalam gereja maupun masyarakat. Dengan demikian, teologi ini merupakan suatu refleksi kritis atas praksis. Jenis teologi kritis atau protes tampaknya menjadi ciri teologi masa kini. Dari berbagai kritik yang dilontarkan tersebut memang harus kita akui adanya kepincangan atau ketidakseimbangan antara teologi dan praksis. Tidak sedikit orang Kristen dan pemimpin gereja yang menguasai dengan sangat baik bermacam-macam doktrin dalam Alkitab, tetapi pengetahuan itu tidak terejawantahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu, tidak mengherankan jika muncul teologi hitam, teologi pembebasan, dan teologi lain yang sejenis, yang berusaha merelevankan Alkitab ke dalam berbagai situasi kehidupan. Usaha para feminis dan juga tokoh pembebasan lainnya untuk membuat Alkitab relevan bagi setiap zaman, ataupun usaha mereka menjadi jembatan penghubung antara zaman Alkitab dengan situasi kontemporer merupakan suatu usaha yang sangat baik. Hanya, patut disayangkan, usaha tersebut lebih menitikberatkan unsur kepentingan manusia dan konteks sehingga mereka tidak segan-segan mengorbankan iman Kristen yang ortodoks. Namun, terlepas dari masalah tersebut, usaha untuk menyeimbangkan teologi dan praksis merupakan usaha yang juga harus dilakukan gereja masa kini.
Sumbangsih teologi feminis juga terasa di dalam gereja. Selama ini tidak sedikit gereja yang melarang kaum wanita mengambil bagian dalam pelayanan. Makin bertumbuhnya gerakan kaum wanita, mau tidak mau memaksa gereja dan para teolog untuk kembali melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai peran wanita dalam gereja. Sedikit demi sedikit gereja mulai membuka diri terhadap sumbangsih yang bisa diberikan oleh kaum wanita. Di lingkungan gereja di Indonesia, ada gereja tertentu yang dahulu "mengharamkan" pelayanan atau jabatan tertentu bagi wanita, tetapi saat ini ada cukup banyak gereja yang mulai membuka diri terhadap wanita. Ada gereja-gereja tertentu yang memberi kesempatan bagi jemaat wanitanya untuk mengambil dalam pelayanan dan yang menahbiskan rohaniwatinya ke dalam jabatan pendeta, suatu hal yang dahulu jarang terjadi. Menurut saya hal ini baik karena tidak sedikit wanita Indonesia pada masa kini yang memiliki bakat, kemampuan, dan tingkat kerohanian yang baik, bahkan juga tidak sedikit yang lebih baik dari pria. Mereka bisa melayani Tuhan sama baiknya dengan pria. Justru dengan natur pria dan wanita yang komplementer, saling melengkapi, memberikan tanda bahwa gereja akan diperkaya dengan adanya partisipasi wanita dalam pelayanan.
Penutup
"Liberation from a patriarchal worldview is never a finished task," ("Pembebasan dari pandangan dunia patriarkhal tidak pernah selesai," - Red.) demikian kata Russell. Saya tidak berani memastikan bagaimana masa depan teologi feminisme di dalam kekristenan atau dalam lingkup lainnya selama beberapa dasawarsa ke depan. Memang saat ini gerakan pemberdayaan kaum wanita muncul di mana-mana bagaikan cendawan pada musim hujan. Namun pertanyaannya, apakah perjuangan wanita-wanita Kristen pada era 1960-an masih akan tetap bergabung dan relevan pada abad ke-21 ini? Atau jika kita ganti pertanyaannya, apakah teologi feminis seperti yang dipaparkan di atas dalam beberapa dasawarsa mendatang masih bisa disebut teologi feminis Kristen? Sulit untuk menjawabnya. Namun, Ruether jauh sebelumnya (tahun 1983) sudah memberikan pernyataan: "The more one becomes a feminist the more difficult it becomes to go to church." ("Semakin seseorang menjadi seorang feminis, semakin sulit seseorang untuk pergi ke gereja." - Red.)
Diambil dan disunting seperlunya dari:
| Judul buku | : | Veritas, Jurnal Teologi dan Pelayanan Volume 4 |
| Judul bab | : | Sebuah Tinjauan terhadap Teologi Feminisme Kristen |
| Judul asli artikel | : | Teologi Feminisme |
| Penulis | : | Lie Ing Sian |
| Penerbit | : | SAAT, Malang 2003 |
| Halaman | : | 272 -- 278 |
Dear e-Reformed Netters,
Feminisme adalah paham yang pergerakannya dimulai sejak akhir abad ke-18, yang menuntut kesetaraan hak dan perlakukan yang adil bagi wanita. Satu hal yang mendasari dan menjadi keyakinan dari pergerakan ini adalah bahwa masyarakat beserta sistem dan tatanan hukum yang ada di dunia ini bersifat patriarki sehingga menyebabkan subordinasi atau penindasan pada kaum wanita. Kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi wanita kemudian menjadi tujuan dari pergerakan kaum feminis demi mengakhiri penindasan terhadap kaum wanita, yang tak jarang juga terjadi dalam gereja dan komunitas Kristen. Tak pelak, feminisme sampai kini masih menjadi suatu perdebatan panjang di kalangan orang Kristen dan gereja-gereja Tuhan, meski tak semua pihak mampu memandang dan menyikapinya dalam kacamata iman dan perspektif yang benar.
Untuk mengetahui lebih banyak mengenai teologi feminisme, publikasi e-Reformed pada bulan Agustus ini akan mengetengahkan sebuah artikel yang berisi pandangan dari beberapa teolog feminis Kristen liberal mengenai feminisme beserta dasar-dasar teologi dari Alkitab yang digunakan untuk mendukung paham dan pergerakan feminisme. Kami berharap, suguhan e-Reformed edisi 167 ini akan semakin membukakan perspektif kita dalam memandang dan menyikapi teologi feminisme, terutama dari sudut pandang Alkitab.
Untuk ikut memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 pada bulan Agustus ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada negara kita yang tercinta ini. Biarlah Tuhan akan terus memberikan kejayaan bagi bangsa dan negara kita, Indonesia!
Pemimpin Redaksi e-Reformed,
N. Risanti
http://reformed.sabda.org
Pendahuluan
"If I were only meant to tend the nest, then why does my imagination sail across the mountains and the seas .... Just tell me where, where is it written what it is I'm meant to be, that I can't dare," (Jika aku ditakdirkan untuk mendiami sangkar, lalu mengapa imajinasiku berlayar mengelilingi pegunungan dan lautan ... Katakan kepadaku, di manakah hal itu tertulis bahwa itu merupakan takdirku, yang tidak dapat kulangkahi. - Red.) demikian sepenggal lirik lagu tema film Yentl, sebuah film musikal yang berkisah tentang seorang gadis Yahudi yang dibesarkan di Eropa Timur pada awal abad kedua puluh. Penggalan lirik lagu di atas adalah sebagian kecil jeritan hati Yentl, gadis belia yang hasratnya untuk mempelajari Talmud terkungkung di balik jeruji patriarkhal Yahudi yang dengan keras melarang wanita belajar agama. Wanita dianggap hanya bisa dan boleh tahu urusan dapur, anak, dan rumah tangga. Kalaupun mereka boleh membaca, jenis bacaan yang "halal" bagi mereka hanyalah roman picisan atau komik bergambar.
Jeritan hati Yentl, lepas dari apakah tokoh dan kisah tersebut adalah rekaan sang pengarang, Isaac Bashevis Singer, atau kisah nyata, bukanlah yang pertama dan satu-satunya terdengar sejak dunia ini diciptakan. Dominasi kaum pria yang, anehnya, telah berlangsung secara mengglobal jauh sebelum era globalisasi, telah menggoreskan luka yang dalam di hati banyak wanita. John Stott menggambarkan kondisi ini dengan kata-kata yang cukup tajam:
For there is no doubt that in many cultures women have habitually been despised and demeaned by men. They have often been treated as mere playthings and sex objects, as unpaid cooks, housekeepers and child-minders, and as brainless simpletons incapable of engaging in rational discussion. Their gifts have been unappreciated, their personality smothered, their freedom curtailed, and their service in some areas exploited, in others refused. (Sebab, tidak ada keraguan bahwa dalam banyak kebudayaan perempuan biasa dihina dan direndahkan oleh laki-laki. Mereka sering diperlakukan hanya sebagai mainan dan objek seks, sebagai koki tidak dibayar, pembantu rumah tangga dan pengawal anak, dan seorang bodoh yang tidak mampu terlibat dalam diskusi rasional. Talenta mereka telah tidak dihargai, kepribadian mereka ditahan, kebebasan mereka dibatasi, dan layanan mereka di beberapa wilayah dieksploitasi, serta ditolak di wilayah lain. - Red.)
Tidak heran jika timbul berbagai reaksi dari kaum wanita, mulai dari yang sekadar memendam rasa tidak puas hingga yang berani bersuara bahkan yang lebih ekstrem, memberontak terhadap tatanan yang telah berurat berakar di masyarakat. Tidak heran pula jika di berbagai penjuru dunia akan menemukan gerakan kaum wanita yang dikenal dengan istilah "feminisme", suatu gerakan yang dilandasi oleh kesadaran kaum wanita bahwa mereka adalah makhluk yang Tuhan ciptakan sederajat dengan pria.
Gerakan ini sangat terasa khususnya dalam beberapa dasawarsa terakhir abad dua puluh, sekaligus telah membawa perubahan yang sangat besar dalam masyarakat pada saat ini. Kaum wanita yang dulunya tidak memiliki posisi yang cukup berarti dan dianggap sebagai kaum lemah dalam masyarakat kini mulai mengedepan. Sejumlah besar wanita memasuki panggung politik dunia saat ini; tidak sedikit yang memegang jabatan penting di perusahaan-perusahaan besar dan sebagian lainnya meraih prestasi puncak dalam bidang pendidikan. Singkatnya, wanita kini memiliki kesempatan dalam dunia kerja dan pendidikan yang lebih luas daripada sebelumnya.
Pengaruh gerakan ini juga merambah ke dalam dunia teologi abad 20. Pada paruh kedua tahun 1960-an, teolog-teolog wanita dan mahasiswi sekolah teologi telah mengembangkan satu genre baru dalam pemikiran Kristen kontemporer yang dikenal sebagai teologi feminis. Teologi ini memiliki spektrum yang luas dan terus berkembang sehingga kalau kita berbicara tentang teologi feminis Kristen, harus jelas teologi feminis Kristen yang mana, liberal, radikal atau evangelikal, karena masing-masing memiliki arah atau penekanan yang berbeda.
Walaupun usianya masih tergolong "muda", tetapi sejak kelahirannya teologi ini telah mengalami perkembangan yang amat pesat dan menjadi teologi yang sangat signifikan pada abad 20. Kendati demikian, hal ini tidak berarti teologi feminis diterima oleh semua pihak. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit orang atau kelompok yang menolak dan mengajukan keberatan terhadap teologi ini, misalnya orang-orang yang menyebut diri sebagai tradisionalis. Keberatan yang paling umum diajukan adalah bahwa teologi feminis bersifat subjektif dan dianggap telah mendistorsi makna teks-teks Alkitab yang menjadi dasar teologi ini. Tidak mengherankan jika teologi feminis mendapat kritik, kecaman dan serangan, bahkan penolakan.
Apakah sebenarnya teologi feminis itu? Mengapa teologi ini mendapat banyak kritik di sana-sini? Apakah teologi ini mendapat dukungan yang cukup dari Alkitab sebagai sumber teologi Kristen yang berotoritas? Untuk menjawab pertanyaan ini, pada halaman-halaman berikut secara singkat kita akan mencoba mendefinisikan feminisme Kristen, kemudian mempelajari bagaimana pandangan feminisme terhadap Alkitab serta metode berteologinya. Mengingat luasnya lingkup feminis maka pembahasan difokuskan pada teologi feminis Kristen liberal yang diwakili oleh Rosemary Radford Ruether, Letty M. Russell, dan Elizabeth Schiissler Fiorenza. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, pada bagian berikut akan kita telusuri lebih dahulu latar belakang historisnya guna lebih memahami pandangan ini.
Latar Belakang Teologi Feminis
Pandangan yang merendahkan wanita bukan hanya ada di luar kekristenan. Di dalam gereja sendiri, tragisnya, sering kali wanita dipandang sebagai harta milik, objek, polusi yang membahayakan, dan yang paling keras adalah wanita dinilai tidak mampu menjadi gambar Allah sehingga mereka dilarang untuk menjadi pemimpin, pengkhotbah, dan pengajar dalam ibadah maupun pelayan di gereja.
Paulus dalam surat-suratnya pun seolah-olah "mengonfirmasi" status dan peran wanita dalam gereja, misalnya di 1 Korintus 14:34-35 dan 1 Timotius 2:12-16. Pada kedua bagian tersebut, Paulus melarang wanita berbicara dan mengajar dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Bahkan, secara tegas, ia menulis bahwa Hawa-lah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Sikap Paulus tersebut sangat memengaruhi cara gereja memperlakukan wanita. Selain oleh ayat-ayat tersebut, cara bapak-bapak gereja memperlakukan wanita juga banyak dipengaruhi oleh ajaran Yunani dan Talmud. Menurut William Barclay, pandangan orang Yahudi yang merendahkan wanita tampak dalam doa pagi pria Yahudi yang terdapat dalam Talmud. Di dalam doanya setiap pagi, seorang Yahudi bersyukur karena Tuhan tidak menciptakannya sebagai seorang kafir, budak, atau wanita. Tertullian, salah seorang bapak gereja, berkata, "You [wanita] are the devil's gateway; you are the unsealer of that (forbidden) tree; you are the first deserter of the divine law ...." ("Anda [wanita] adalah pintu setan; Andalah pendobrak pohon terlarang, Andalah pembelot pertama dari hukum ilahi ...." - Red.) Tidak mengherankan jika pada zaman bapak gereja, kaum wanita hampir-hampir tidak memiliki bagian di dalam gereja. Wanita pada masa itu dianggap rendah dan berada di bawah dominasi pria. Keadaan ini terus berlanjut selama berabad-abad tanpa ada perubahan.
Pada abad pertengahan, kaum wanita mulai menyadari bahwa mereka dimarginalkan dalam urusan gereja dan masyarakat; kesempatan yang mereka miliki sangat terbatas dan tempat yang tersedia bagi mereka hanyalah dalam rumah tangga. Kesadaran akan keadaan ini mulai membawa sedikit angin perubahan. Sejumlah wanita tampil sebagai penulis-penulis spiritual dan mistik pada masa ini. Beberapa karya tulis mereka menunjukkan adanya pengertian yang mendalam tentang isu-isu filsafat. Hanya, karya tulis tersebut tidak dalam bentuk seperti tulisan para teolog gereja, tetapi lebih bersifat kontemplatif yang memperlihatkan pendekatan mereka terhadap masalah-masalah kehidupan, di mana kunci jawabannya mereka cari di dalam hal-hal spiritual.
Keadaan kaum wanita secara perlahan-lahan mengalami sedikit perubahan pada zaman Pencerahan. Semangat abad Pencerahan memberi dampak besar bagi bangkitnya para wanita, terutama di Eropa. Beberapa wanita tampil ke permukaan dan melahirkan karya tulis ilmiah tentang wanita. Gagasan kesetaraan wanita dengan pria dituangkan dalam tulisan-tulisan mereka dalam bentuk esai, disertasi, dan sebagainya. Pada abad berikutnya, muncul beberapa wanita terkemuka yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang sains dan filsafat; sebagian lainnya memainkan peran penting di bidang seni, pendidikan, dan politik.
Gerakan ini makin terasa pada abad ke-20, khususnya di Barat. Di Amerika Serikat yang menjadi katalisator gerakan wanita modern adalah karya monumental Betty Friedan, The Feminine Mystique (1963), yang memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat di negara tersebut. Pengaruhnya dapat disejajarkan dengan karya Charles Darwin, The Origin of the Species. Sejak saat itu, gerakan ini seolah tak terbendung lagi. Kini, gerakan feminisme dapat kita jumpai di belahan bumi mana pun sehingga tidak heran jika kita mengenal adanya "black feminist theology" di Afrika, feminis Islam di Indonesia, feminis Yahudi, dan sebagainya.
Dari paparan di atas tampak bahwa teologi feminisme lahir sebagai reaksi protes terhadap penindasan atas kaum wanita yang berlangsung di dalam dan luar gereja selama berabad-abad. Teolog-teolog feminis sendiri yakin bahwa pendorong gerakan mereka berakar dari pengajaran PB tentang bagaimana seharusnya orang Kristen berelasi satu dengan yang lain. Model relasi orang Kristen, khususnya pria dan wanita tidak bersifat hierarki, melainkan kesederajatan yang sempurna dan tidak boleh ada lagi peran dalam masyarakat, gereja ataupun di rumah yang berdasar pada gender.
Definisi Feminisme
Apakah feminisme dan teologi feminis itu? Untuk mendefinisikannya bukanlah hal yang mudah karena tokoh-tokoh feminis itu sendiri sangat beragam. Menurut Marcia Bunge, ada perbedaan suara antara feminis yang satu dengan yang lain, yang terlihat melalui karya tulis mereka, baik buku-buku maupun artikel-artikel, yang belakangan ini semakin marak. Dengan bervariasinya tokoh, tulisan serta pandangan mereka, sulit untuk menentukan nuansa definisi feminisme yang jelas karena tidak ada kanon tradisi feminis yang normatif ataupun rumusan kredo yang jelas.
Kendati sangat beragam dalam struktur, bentuk, dan penekanan, tetapi itu tidak berarti sama sekali tidak ada kesamaan di antara para feminis. Pamela Dickey Young mencirikan empat tema yang mempersatukan gerakan para feminis di seluruh dunia, yaitu: pertama, teologi Kristen tradisional bersifat patriarkhal. "It has been written, almost totally, by men. It has been formulated, despite claims to universality, as though maleness were the normative form of humanity." ("Telah ditulis, hampir sepenuhnya, oleh laki-laki. Ini telah dirumuskan, meskipun klaim universalitas, seakan kelelakian adalah bentuk normatif kemanusiaan." - Red.) Kedua, teologi tradisional telah mengabaikan kaum wanita serta pengalaman mereka. Ketiga, natur teologi yang patriarkhal telah memberikan konsekuensi yang merusak bagi wanita. Keempat, sebagai solusi atas ketiga masalah di atas, wanita harus menjadi teolog yang memulai usaha teologis mereka. ... women must become equal shapers of the theological enterprise. (... para wanita harus menjadi pembentuk yang setara atas masalah teologis. - Red.) Karena itu, menurut Young, setiap doktrin serta konsep teologis harus diuji kembali dari sudut kesadaran kaum wanita yang tertindas. Hal senada juga diungkapkan oleh Tolbert, "... while others understand feminism to be primarily a movement toward human equality in which oppressed and oppressor are finally reconciled. (... sementara yang lain memahami feminisme pada dasarnya merupakan gerakan menuju kesetaraan manusia ketika yang tertindas dan penindas akhirnya didamaikan. - Red.)
Dari paparan singkat di atas tampak bahwa penekanan feminisme ialah "penindasan", "patriarkhal", dan "kesetaraan". Ketiga hal ini merupakan problem yang harus dihadapi oleh wanita; kaum wanita harus berjuang melawan penindasan yang diakibatkan oleh sistem patriarkhal guna mencapai kesetaraan dengan pria. Dengan kata lain, perjuangan kaum wanita pada dasarnya ialah perjuangan untuk meraih kebebasan. Secara ringkas, bisa disimpulkan bahwa feminisme pada hakikatnya adalah gerakan pembebasan kaum wanita dari sistem yang selama ini membuat posisi mereka berada di marginal, sedangkan teologi feminis bisa disebut sebagai usaha untuk menjelaskan kembali iman Kristen dari perspektif wanita sebagai kelompok yang tertindas.
Teologi Feminisme
Pandangan terhadap Alkitab
Kalau kita berbicara mengenai teologi seseorang atau sekelompok orang, salah satu pertanyaan yang penting dan perlu diajukan adalah bagaimana pandangan orang atau kelompok orang tersebut terhadap Alkitab? Apakah Alkitab diterima sebagai firman Allah yang berotoritas? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut setidaknya menunjukkan corak teologi yang dianut seseorang atau sekelompok orang tersebut. Pandangan Fiorenza mengenai Alkitab diungkapkan dalam kalimat berikut:
A feminist hermeneutics cannot trust or accept Bible and tradition simply as divine revelation. Rather it must critically evaluate them as patriarchal articulations, since even in the last century Sarah Grimke, Matilda Joslyn Gage, and Elizabeth Cady Stanton had recognized that biblical texts are not the words of God but the words of men. (Sebuah hermeneutika feminis tidak dapat memercayai atau menerima Alkitab dan tradisi hanya sebagai wahyu ilahi. Sebaliknya, hermeneutik feminis harus kritis menilai keduanya sebagai artikulasi patriarkhal, terlebih karena Sarah Grimke, Matilda Joslyn Gage, dan Elizabeth Cady Stanton pada abad terakhir telah mengakui bahwa teks Alkitab bukanlah kata-kata Tuhan, tetapi kata-kata manusia. - Red.)
Selanjutnya, ia mengatakan: "Feminist interpretation therefore begins with hermeneutics of suspicion that applies to both contemporary androcentric interpretations of the Bible and the biblical texts themselves." (Oleh karena itu, interpretasi feminis dimulai dengan hermeneutika kecurigaan yang berlaku untuk kedua interpretasi androsentrik kontemporer Alkitab dan teks-teks alkitabiah sendiri. - Red.). Sedangkan Ruether mengalimatkan demikian: "The Bible was shaped by males in a patriarchal culture, so much of its revelatory experiences were interpreted by men from a patriarchal perspective." ("Alkitab dibentuk oleh laki-laki dalam budaya patriarkhal, begitu banyak pengalaman pewahyuan yang ditafsirkan oleh manusia dari perspektif patriarki." - Red.) Secara ringkas yang ingin disampaikan kedua tokoh ini adalah Alkitab tidak boleh diterima mentah-mentah sebagai firman Allah karena banyak unsur manusia (baca: pria) di dalamnya.
Jika ditanya mengenai inspirasi Alkitab, para feminis akan segera menjawab bahwa mereka percaya inspirasi. Akan tetapi, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa itu artinya mereka masih berada di jalur iman Kristen yang ortodoks. Simak pernyataan Russell berikut: "The Bible is especially dangerous if we call it 'the Word of God' and think that divine inspiration means that everything we read is right." (Alkitab secara khusus bersifat berbahaya jika kita menyebutnya "Firman Allah" dan berpikir bahwa inspirasi ilahiah berarti bahwa segala sesuatu yang kita baca adalah benar. - Red.) Menurut Russell, inspirasi ilahi Alkitab berarti bahwa Roh Allah memiliki kuasa untuk membuat kisah Alkitab berbicara kepada kita dari iman menuju kepada iman. Alkitab diterima sebagai firman Allah apabila komunitas iman memahami Allah berbicara kepada mereka di dalam dan melalui berita Alkitab. Pandangan "miring" tersebut tidak aneh karena kelompok feminis yang menyebut diri evangelikal pun memiliki keyakinan serupa:
[T]he Spirit of God is the ultimate author of all Scripture. The Christian church, therefore, has rightly understood the phrase "the inspiration - of Scripture" to indicate that in and through the words employed by the biblical writers God has given his word to mankind. ... the Bible is a divine/human book ... as human, this light of revelation shines in and through the "dark glass" (1 Cor. 13:12) of the "earthen vessels" (2 Cor. 4:7) who were the authors of its content at the human level. (Roh Allah adalah penulis utama dari semua Kitab Suci. Gereja Kristen, oleh karena itu, telah benar memahami frase "inspirasi dari Kitab Suci" untuk menunjukkan bahwa di dalam dan melalui kata-kata yang digunakan oleh para penulis Alkitab, Allah telah memberikan firman-Nya kepada umat manusia .... Alkitab adalah sebuah buku yang ilahiah/manusia ... bagi manusia, cahaya wahyu ini bersinar di dalam dan melalui "kaca gelap" (1 Kor 13:12.) dari "bejana tanah liat" (2 Korintus 4:7), yang merupakan penulis isinya pada tingkat manusia. - Red.)
Menurut kelompok ini, Alkitab diinspirasikan oleh Allah dalam pengertian bahwa di dalam dan melalui kata-kata yang digunakan oleh penulis Alkitab, Allah memberikan firman-Nya. Allah memakai manusia yang terbatas untuk menyatakan kehendak-Nya. Firman Allah sempurna, tetapi manusia sebagai penulis Alkitab, terbatas. Jadi, ada peluang bagi ketidaksesuaian antara firman Allah yang kekal dan kata-kata yang digunakan oleh para penulis Alkitab. Atau, dengan kata lain, Alkitab bersifat falibel serta tunduk pada keterbatasan manusia dalam menuangkan maksud Allah dalam kata-kata.
Hal serupa diungkapkan oleh Russell ketika ia berbicara tentang otoritas Alkitab. Alkitab berotoritas dalam kehidupannya karena Alkitab memahami pengalamannya dan berbicara kepadanya tentang makna dan tujuan kemanusiaannya di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, meskipun Alkitab ditulis dari sudut pandang patriarkhal, dan juga terdapat ketidakkonsistenan atau kontradiksi, tetap saja Alkitab berotoritas dalam kehidupannya karena kisah Alkitab membawanya kepada satu visi tentang ciptaan baru. Kalau boleh saya simpulkan, otoritas Alkitab menurut Russell adalah otoritas yang pragmatis, tidak penting apakah Alkitab bisa salah atau tidak, yang penting baginya adalah Alkitab itu memiliki kebergunaan dalam kehidupannya.
Bertitik tolak dari sini, teolog feminis berani mengatakan bahwa Paulus tak memiliki pandangan yang konsisten tentang wanita. Hal ini terjadi karena Alkitab dibentuk oleh kaum pria dari budaya patriarkhal sehingga banyak pengalaman wahyunya diinterpretasi dan ditulis dari perspektif patriarkhal. Itu sebabnya, mengapa Paulus kadang-kadang menempatkan wanita dalam posisi lebih rendah daripada pria, tetapi kadang-kadang juga sebaliknya. Jadi, ketika kita membaca Alkitab, kita tidak boleh mengabsolutkan budaya pada saat Alkitab ditulis dan untuk memperoleh kebenaran Allah, kita harus menghilangkan unsur-unsur budaya ketika melakukan interpretasi.
Catatan: partriarkhal --> patrilineal: mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat pria saja, bapak (KBBI).
Diambil dan disunting seperlunya dari:
| Judul buku | : | Veritas, Jurnal Teologi dan Pelayanan Volume 4 |
| Judul bab | : | Sebuah Tinjauan terhadap Teologi Feminisme Kristen |
| Judul asli artikel | : | Teologi Feminisme |
| Penulis | : | Lie Ing Sian |
| Penerbit | : | SAAT, Malang 2003 |
| Halaman | : | 263 -- 272 |
Prinsip yang harus diingat oleh seorang pengkhotbah, yaitu: "Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus " (2 Korintus 4:5). Pusat pemeberitaan khotbah adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apapun jenis-jenis khotbah, jika pusat pemberitaannya bukan Yesus, itu bukan ajaran yang sehat. Karena khotbah yang disampaikan entah satu ayat atau satu perikop, bukanlah penentu apakah khotbah itu alkitabiah atau tidak alkitabiah. Termasuk singkat atau lamanya durasi khotbah bukan sebagai jaminan, bahwa khotbah itu berkualitas baik dan sehat.
Khotbah yang alkitabiah dan sehat adalah mengekspos bagian Akitab secara sistematik ayat demi ayat atau paragraf demi paragraf. Prinsip ini membutuhkan ketrampilan khususuntuk meneliti (eksegese) teks Alkitab tersebut, sehingga menemukan makna sebenarnya dari teks itu dan melihat relevansinya serta menjelaskan sesuai dengan garis besar khotbahnya. Gordon D. Fee mengatakan, bahwa: penafsiran Alkitab (eksegesis) dibutuhkan karena "ketegangan" yang ada diantara relevansi kekalnya dengan keistimewaan historisnya. Artinya selain menemukan makna sebenarnya, melalui studi eksegesis ini, pengkotbah terhindar dari kesalahan-kesalahan eisegesis. Karena godaan besar bagi pengkotbah yang fasih berbicara, adalah tidak mau meneliti bagian teks Alkitab dengan sabar dengan mempertimbangkan prinsip hermeneutika yang sehat. Sehingga isi khotbah yang disampaikan terdengar seperti alkitabiah, tetapi bukan alkitabiah yang sesuai prinsip hermenutika. Tindakan ini disebut, menggeser berita Alkitab dan menggantikannya dengan berita-berita lain - termasuk pengalaman sendiri. Karena itu, gereja yang besar belum tentu khotbah-khotbahnya baik dan sehat. Tetapi gereja yang sehat secara iman, pasti memiliki pengajaran/khotbah yang benar sesuai prinsip Alkitab. Ini tidak bisa dibohongi.
| Buku | : | Jurnal Teologi STULOS |
| Judul Artikel | : | Khotbah harus Alkitabiah |
| Penulis | : | Harapan Sianturi |
| Halaman | : | 101-102 |
Anda tertarik dengan dunia tulis-menulis dan memerlukan referensi berkualitas untuk mengembangkan kemampuan tulis-menulis Anda?
Dear e-Reformed Netters,
Reformasi gereja abad 15 lahir sebagai upaya untuk mereformasi gereja Katolik, diprakarsai oleh umat Katolik Eropa Barat yang menentang doktrin-doktrin palsu dan malapraktik gerejawi, khususnya ajaran dan penjualan indulgensi, serta simoni, jual-beli jabatan rohaniwan. John Calvin adalah salah satu tokoh reformasi yang hidup di tengah gejolak masa itu. Dalam perjuangannya, ia mendapat dukungan dari beberapa tokoh reformasi, tetapi tak jarang ia juga mendapat kecaman dari berbagai pihak yang menentangnya.
Untuk mengetahui siapa saja orang yang mendukung maupun mengecam Calvin, e-Reformed edisi bulan Juli ini akan menyajikan sebuah artikel berjudul "Galeri Pendukung dan Penentang Calvin". Melalui artikel ini, kita akan mengenal beberapa tokoh lain yang berpengaruh dalam perjuangan John Calvin mereformasi gereja pada masa itu. Kiranya kita boleh semakin mengerti bahwa iman yang sejati kepada Kristus tidak mudah untuk diperjuangkan dan akan terus mendapat tantangan dan ujian sepanjang zaman, seperti yang di alami oleh John Calvin semasa hidupnya. Soli Deo Gloria.
Pemimpin Redaksi e-Reformed,
Ayub
< ayub(at)in-christ.net >
< http://reformed.sabda.org >
Olivetan (1503 -- 1535)
Nama aslinya adalah Pierre Robert, dan ia adalah sepupu Calvin. Olivetan, yang berarti "Minyak Tengah Malam", adalah nama panggilan yang diperolehnya karena kebiasaannya belajar sampai larut malam. Menurut Beza, Olivetanlah yang mengobarkan api penginjilan dalam hati Calvin.
Walaupun telah saling mengenal sejak di Noyon, kampung halaman Calvin, kedua sepupu ini baru menjadi akrab ketika sama-sama belajar di Paris dan Orleans. Olivetan yang sudah menjadi seorang Protestan membangkitkan kecurigaan pemerintah sehingga pada tahun 1528, ia terpaksa melarikan diri ke tempat Martin Bucer di Strasbourg.
Pada tahun 1532, masyarakat Kristen Waldensia di daerah Piedmont, Italia, menggabungkan diri dengan gerakan reformasi. Olivetan mengunjungi kaum Waldensia, dan ia ditugaskan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam Bahasa Perancis. Ketika Calvin melarikan diri dari Perancis ke Basel pada tahun 1535, Olivetan sedang berada di sana untuk menyelesaikan proyek perintisnya tersebut. Calvin mungkin membantu sepupunya dalam tahap terakhir penerjemahan Perjanjian Baru. Calvin menulis kata pengantar dalam Bahasa Perancis dan Bahasa Latin yang untuk pertama kalinya mencerminkan dengan jelas semangat penginjilannya.
Setelah membantu memenangkan Jenewa bagi gerakan reformasi pada tahun 1533 sampai 1535, Olivetan kembali ke kaum Waldensia di Italia. Ia meninggal pada usia 32 tahun. Hubungan kedua sepupu itu tampaknya cukup dekat karena Olivetan mewariskan perpustakaannya kepada Calvin.
Lefevre D'Etaples (1455 -- 1536)
Dalam masa pertumbuhan rohaninya, Calvin mulai mengenal gerakan reformasi Perancis yang dipelopori oleh Lefevre D'Etaples, seorang ahli Alkitab yang agung. Lefevre mempelajari Alkitab secara intensif, lalu menyimpulkan bahwa Alkitab haruslah menjadi satu-satunya sumber otoritas. Ia menganjurkan cara interpretasi Alkitab "literal-spiritual". Menurut argumentasi Lefevre, satu-satunya arti yang layak bagi ayat-ayat Alkitab adalah arti yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Martin Luther sangat dipengaruhi oleh cara interpretasi "literal-spiritual" ini.
Bersumber pada surat-surat rasul Paulus, Lefevre juga akhirnya menyadari bahwa manusia diselamatkan hanya oleh belas kasihan dan anugerah Allah yang diterima dengan iman saja. Perbuatan baik maupun jasa manusia sama sekali tidak berperan dalam keselamatan. Ia memelopori doktrin predestinasi yang ketat; pandangannya mengenai pembenaran hanya melalui iman mendahului pandangan Luther.
Ketika mempelajari Alkitab, Lefevre merasa takjub karena tidak menemukan istilah paus, indulgensia (surat pengampunan dosa), api penyucian, tujuh sakramen, wajib selibat pastor, atau penyembahan kepada Maria. Tidak mengherankan, ia dituduh bidat di Sorbonne pada tahun 1521. Setelah itu, Lefevre bergabung dengan muridnya, Bishop Briconnet, untuk membantu membentuk keuskupan di Meux. Guillaume Farel, yang belakangan memegang peranan penting bagi Calvin dan Jenewa, juga berada di Meux. Pada tahun 1525, kebencian terhadap gerakan reformasi Lefevre semakin meningkat sehingga ia terpaksa pergi ke Strasbourg dan tinggal di sana beberapa lama. Sekembalinya dari Strasbourg, ia tinggal di Nerac sampai tutup usia, dalam perlindungan Marguerite d'Angouleme, saudari Raja.
Calvin datang ke Nerac sebagai seorang pelarian dari kekuasaan Roma Katolik; di sana ia bertemu dengan Lefevre yang sudah tua pada musim semi tahun 1534. Menurut berita, Lefevre mengatakan bahwa Calvin kelak akan menjadi "sebuah instrumen dalam mendirikan Kerajaan Allah di Perancis". Nyata bahwa pertemuan dengan Lefevre itu meyakinkan Calvin bahwa reformasi tidak akan berhasil jika ia tetap berada dalam Gereja Roma Katholik. Tak lama kemudian, Calvin memutuskan untuk memisahkan diri dari Roma.
Francis I (1515 -- 1547)
Francis I adalah Raja Perancis yang berkuasa pada masa awal gerakan reformasi Calvin. Dalam hampir seluruh masa pemerintahannya, Francis terlibat peperangan melawan Charles V, Kaisar dan Holy Roman Empire (kekaisaran pada zaman itu yang wilayahnya mencakup Jerman, Belgia, Belanda, Swiss, dan Austria), sehingga ia tidak dapat mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal agamawi. Pada awalnya, Francis sangat toleran kepada para tokoh reformasi Perancis karena pengaruh saudarinya, Marguerite d' Angouleme. Francis bahkan memiliki hubungan yang baik dengan Lefevre D'Etaples, perintis gerakan reformasi di Perancis. Akan tetapi, semua itu berubah pada bulan Oktober 1534.
Surat Calvin yang terkenal, yang menjadi kata pengantar untuk edisi pertama buku Institutio, ditujukan kepada Francis I. Raja ini sangat marah karena protes kaum Protestan Perancis, yang dikenal sebagai "Peristiwa Plakat". Pada pagi hari tanggal 18 Oktober 1534, di seluruh Paris kaum Protestan membagikan selebaran yang mencela misa Katolik. Salah satunya bahkan ditempelkan di pintu kamar tidur Raja. Francis menunjukkan kemarahannya dengan mengikuti suatu prosesi agamawi menuju Katedral Notre Dame, yang melambangkan penyucian Paris dari kebencian. Akan tetapi, kemarahan Raja tidak cukup sampai di situ. Ia meresmikan suatu peraturan untuk menganiaya kaum Protestan; peraturan ini berlaku sampai Dekrit Nantes tahun 1598. Ratusan kaum Protestan dipenjarakan oleh Francis, dan 35 orang dibakar, termasuk beberapa sahabat Calvin. Buku Institutio ditulis oleh Calvin dalam ingatan akan para martir Perancis ini. Dalam suratnya, Calvin menulis bahwa buku Institutio ditulis untuk "membersihkan nama saudara-saudaraku yang kematiannya berharga di mata Tuhan".
Francis juga berperan dalam kedatangan Calvin ke Jenewa. Calvin tidak dapat langsung menuju Strasbourg seperti yang semula direncanakan karena Francis sedang berperang melawan Charles V, kaisar dari Holy Roman Empire, dan terpaksa melakukan perubahan arah yang bersejarah ke Jenewa itu.
Guillaume Farel (1489 -- 1565)
Farel adalah orang yang membujuk Calvin, yang ketika itu masih muda, pemalu dan enggan, untuk melayani dalam gerakan reformasi di Jenewa. Calvin yang bermaksud hanya menginap semalam di Jenewa ditahan oleh Farel "bukan terutama dengan nasihat dan desakan", tulis Calvin, "tetapi dengan kata-kata menakutkan yang saya rasakan seolah-olah Tuhan dan surga menahan saya dengan tangan-Nya yang kuat". Si rambut merah yang berapi-api, Farel, bergabung dengan gerakan reformasi Perancis yang dipimpin oleh Lefevre D'Etaples. Ketika terpaksa melarikan diri karena ancaman penganiayaan pada tahun 1523, Farel memimpin sekelompok penginjil untuk berkhotbah terutama di daerah Swiss yang berbahasa Perancis. Ia juga berada di pusat gerakan penginjilan yang membawa kota Bern dan kota Jenewa ke dalam pelukan Protestan. Setelah Farel berhasil membujuk Calvin untuk menetap di Jenewa, mereka mengadakan banyak gerakan reformasi di kota itu. Mungkin Farel adalah teman terdekat Calvin pada masa itu. Mereka mengalami banyak hal bersama; mereka sama-sama diusir dari Jenewa pada tahun 1538. Karena dibujuk lagi oleh Farel, Calvin kembali ke Jenewa pada tahun 1541. Setelah itu, Farel pergi ke Neuchatel dan terus bekerja sama dengan Calvin yang berada di Jenewa.
Persahabatan mereka menjadi renggang pada tahun 1558 ketika Farel yang telah berusia 69 tahun menikah dengan seorang gadis muda. Calvin menolak hadir dalam upacara pernikahan, tetapi persahabatan mereka tidak putus. Salah satu surat terakhir Calvin ditulis untuk Farel, dan isinya meminta Farel "untuk mengingat persahabatan kita". Walaupun sudah tua dan lemah, Farel mengunjungi sahabatnya itu menjelang Calvin meninggal pada tahun 1564. Setahun kemudian, Farel menyusul Calvin.
Martin Bucer (1491 -- 1551)
Bucer adalah guru dan mentor Calvin dalam banyak hal. Semasa pengasingannya dari Jenewa, Calvin berada di bawah pengaruh Bucer di Strasbourg. Calvin diminta datang oleh jemaat berbahasa Perancis di Strasbourg, dan kemudian kedua tokoh reformasi itu menjadi sahabat. Selama 3 tahun masa pertumbuhannya (1538 -- 1541), Calvin berguru pada Bucer. Ia menyerap pandangan-pandangan Bucer mengenai predestinasi, organisasi gereja, dan oikoumene.
Bucer menjadi seorang Protestan ketika mendengar pembelaan Martin Luther dalam Pertentangan Heidelberg pada tahun 1518. Tak lama setelah itu, Bucer, Matthew Zell, Wolfgang Capito, dan Casper Hedio memimpin gerakan reformasi di Strasbourg. Bucer terkenal karena usahanya mempertemukan Ulrich Zwingli dan Martin Luther dalam hal Perjamuan Malam Terakhir. Walaupun gagal, Bucer meneruskan usahanya untuk mempersatukan kaum Lutheran dengan cabang-cabang reformasi dalam Protestan.
Ia diasingkan dari Strasbourg pada masa Interim Augsburg pada tahun 1548 dan pergi berlayar ke Inggris untuk membantu Archbishop Cranmer dalam gerakan reformasi Inggris. Bucer diangkat menjadi profesor Regius di Cambridge dan memengaruhi penulisan Buku Doa Umum pada tahun 1549. Pengaruhnya menghilang setelah ia meninggal di Inggris pada tahun 1551.
Diambil dan disunting dari:
| Judul buku | : | Momentum |
| Judul asli artikel | : | Galeri Pendukung & Penentang Calvin |
| Penulis | : | Tidak dicantumkan |
| Penerbit | : | LRII, Jakarta 1996 |
| Halaman | : | 46 -- 49 |
Kesempatan Bergabung dalam Pelayanan di YLSA
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) membuka kesempatan bagi para pengunjung situs untuk bergabung melayani Tuhan melalui dunia internet.
-
DOA - Menjadi Pendoa bagi YLSA
Komitmen: "Saya berjanji berdoa bagi pelayanan Tuhan di YLSA. Untuk itu saya akan bergabung dengan komunitas YLSA untuk mendapatkan pokok-pokok doa YLSA."
Dear e-Reformed Netters,
Apakah filsafat memiliki peran dalam teologi? Pemakaian filsafat dalam disiplin teologi memiliki sejarah yang panjang, dan sering kali diterima dengan rasa curiga dan was-was oleh banyak kalangan gereja. Mengapa demikian? Sebab, filsafat dianggap memiliki potensi membuat orang teracuni dalam memahami kebenaran Alkitab. Dalam edisi kali ini, e-Reformed menyajikan sebuah artikel yang ditulis oleh Kalvin S. Budiman, yang membahas kiprah seorang tokoh utama dalam sejarah gereja pada abad pertengahan, Thomas Aquinas, yang terkenal karena tafsirannya terhadap tulisan-tulisan filsuf besar Yunani, Aristoteles, dan karena usahanya untuk memakai filsafat dalam teologi.
Dalam perkembangannya, Aquinas lebih diingat sebagai seorang filsuf ketimbang seorang teolog, apalagi penafsir Alkitab. Padahal jabatan yang diemban oleh Aquinas semasa hidupnya adalah sebagai baccalaureus biblicus dan magister in theologia. Khususnya di kalangan kaum Injili, Aquinas memiliki reputasi yang kurang baik karena dianggap telah mencemari kemurnian Injil atau teologi Kristen dengan racun pemikiran manusia atau filsafat. Hal ini mungkin mengusik kita untuk mengenal kiprah seorang Aquinas dalam usahanya memakai filsafat dalam teologi. Mari menyimak bersama artikel berikut ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Soli Deo Gloria.
Pemimpin Redaksi e-Reformed,
Ayub
< ayub(at)in-christ.net >
http://reformed.sabda.org
Dalam membangun teologinya, Aquinas mencoba untuk menghindari dua ekstrem. Di satu pihak adalah dari Averroes, seorang filsuf dan teolog Islam yang hidup satu abad sebelum Aquinas. Bagi Averroes, filsafat Aristoteles adalah klimaks perkembangan filsafat Yunani. Akan tetapi, dalam beberapa topik, filsafat Aristoteles bertentangan dengan teologi Islam. Averroes berpendapat bahwa kebenaran dalam teologi dan kebenaran dalam filsafat sifatnya berbeda. Itu sebabnya, menurut Averroes, apa yang benar menurut filsafat, bisa salah menurut teologi. Sebaliknya, apa yang benar menurut teologi, bisa salah menurut filsafat. Misalnya, menurut filsafat Aristoteles, roh manusia sifatnya tidak kekal. Hal ini benar dalam filsafat karena menurut Averroes, Aristoteles memakai pembuktian secara akali. Sedangkan di dalam teologi Islam, roh manusia dikatakan kekal karena didasarkan pada wahyu Allah. Dengan demikian, bagi Averroes, dua pernyataan yang bertentangan, satu dari filsafat dan satu lagi dari teologi, dua-duanya bisa benar. Aquinas menolak pemahaman semacam ini karena bagi dia, hanya ada satu kebenaran yang berasal dari satu sumber, yaitu Allah sendiri. Kebenaran dalam filsafat mestinya tidak bertentangan dengan kebenaran dalam teologi. Jika bertentangan, filsafat harus ditundukkan di bawah terang teologi.
Di lain pihak, ekstrem lain yang Aquinas hindari adalah pendapat dari kelompok Franciscan pada zamannya, seperti Bonaventura. Sama seperti Aquinas, Bonaventura juga percaya hanya ada satu kebenaran karena hanya ada satu sumber kebenaran, yaitu Tuhan sendiri. Yang berbeda adalah bagaimana Bonaventura mengaplikasikan prinsip ini ke dalam konteks relasi antara filsafat dan teologi. Bonaventura percaya bahwa pengetahuan yang sejati sumbernya adalah iluminasi ilahi. Tanpa pencerahan dari iman, kebenaran yang seseorang pegang bukanlah kebenaran yang sejati. Walaupun ia mengakui bahwa filsafat seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles mengandung kebenaran, tetapi itu bukanlah kebenaran yang sejati. Berangkat dari pemahaman ini, Bonaventura tidak memberi tempat untuk Aristoteles dalam teologinya.
Aquinas mengakui bahwa filsafat sifatnya terbatas, bahkan juga mengandung "sisi gelap". Ia juga mengakui bahwa walaupun filsafat memiliki beberapa kesamaan dengan teologi, filsafat juga sering kali berseberangan. Untuk mengatasi fakta ini, Aquinas menolak dua jalan keluar di atas. Ia setuju dengan Bonaventura bahwa filsafat harus ditundukkan di bawah terang iman, tetapi ia tidak setuju dengan Bonaventura bahwa kemudian ia harus membuang filsafat begitu saja. Menurut Aquinas, kedua bidang studi ini mesti dibedakan menurut hakikat (nature) dan ruang lingkupnya (scope). Filsafat dan teologi adalah seperti akal dan wahyu, keduanya tidak bertentangan kalau masing-masing hakikatnya dimengerti dengan tepat. Akal budi manusia pada hakikatnya hanya mendemonstrasikan kebenaran sejauh kebenaran itu berkaitan dengan dunia ciptaan ini. Sementara itu, kebenaran yang berasal dari pewahyuan ilahi yang diterima melalui iman sifatnya melampaui kebenaran yang berasal dari akal budi manusia. Dengan kata lain, bagi Aquinas, sumber kebenaran hanya satu, tetapi cara untuk manusia mencapai pengetahuan, bentuknya bermacam-macam, bergantung pada objeknya. Salah satunya adalah melalui proses berpikir (filsafat), tetapi yang utama adalah melalui pewahyuan (teologi). Asalkan akal budi diletakkan sesuai dengan tempat dan kapasitasnya, baik itu filsafat maupun ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, hasil pemikiran akal budi manusiawi dapat dimanfaatkan dalam teologi. Dalam salah satu bukunya, Summa Contra Gentiles, Aquinas berkata, "Cara seseorang menyampaikan kebenaran tidak selalu sama, dan, seperti yang dengan tepat dikatakan oleh sang filsuf [Aristoteles], 'orang yang berpendidikan tahu bagaimana menggapai pemahaman sesuai konteks penyelidikannya.'" Artinya, setiap disiplin ilmu: matematika, biologi, tata bahasa, termasuk filsafat, masing-masing memiliki cara dan batasan pengetahuan yang dapat dihasilkan karena objeknya yang berbeda-beda. Tiap-tiap disiplin ini dapat memberikan sumbangsih pada teologi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Jadi, dalam berteologi, akal kita dapat mempelajari kebenaran tentang Allah sebatas, misalnya, tentang keberadaan Allah atau tentang beberapa sifat Allah, tetapi kebenaran-kebenaran teologis lainnya, seperti Allah Tritunggal, letaknya di luar jangkauan filsafat atau daya nalar manusia. Kita menerima Allah Tritunggal sesuai kapasitas akal kita, tetapi kita tidak mendasarkan pemahaman kita tentang Tritunggal pada akal budi kita, melainkan pada wahyu Allah. Aquinas melihat teologi sebagai sebuah pengetahuan (science), sama seperti pengetahuan-pengetahuan lainnya, tetapi teologi sifatnya kudus (sacred science). Teologi memiliki kualitas sebagai ilmu pengetahuan, sama seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, tetapi bedanya adalah teologi berkaitan erat dengan iman kita kepada Allah. Teologi adalah seperti "jalan" yang membawa manusia kembali kepada Allah. Teologi membahas tentang Allah dan segala hal yang bersangkut paut dengan Allah sebagai yang memulai (beginning) dan tujuan (end) keberadaan segala hal tersebut. Dalam pembukaan "Summa Theologiae", Aquinas menulis: "Teologi tidak membahas tentang Allah dan ciptaan secara seimbang. Yang pertama dan utama, teologi adalah tentang Allah, kemudian tentang ciptaan sejauh ciptaan bergantung pada Allah sebagai yang mengawali dan yang dituju." Pengetahuan-pengetahuan manusiawi lainnya (filsafat, matematika, seni, dan lain sebagainya) sifatnya berdikari (independent) dan tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran dalam teologi, tetapi sifatnya terbatas dibandingkan dengan teologi. Bahkan, bagi Aquinas, hanya dari kacamata teologilah seseorang dapat menyatukan kebenaran-kebenaran dalam berbagai bidang studi yang manusia pelajari. Di samping itu, menurut Aquinas, teologi (sacred science) melampaui pengetahuan-pengetahuan (science) manusia lainnya karena hanya teologi yang mencakup aspek kontemplatif dan praktis. Artinya, teologi membawa manusia ke dalam kebenaran-kebenaran abstrak yang sifatnya ilahi, tetapi juga mendorong manusia untuk mengaplikasikan kebenaran-kebenaran tersebut dalam perbuatan hidup sehari-hari. Tidak heran jikalau Aquinas menegaskan bahwa teologi sama dengan hikmat atau wisdom karena hanya teologi yang mempertimbangkan penyebab yang tertinggi (Allah) dan segala ciptaan di dalam relasinya dengan Allah.
Bagi Aquinas, segala filsafat dan ilmu pengetahuan manusia lainnya yang dibicarakan oleh Aristoteles atau para filsuf lainnya bersangkut paut dengan metafisika dalam wilayah dunia ciptaan Allah. Teologi mencoba memberikan penjelasan tentang realitas ciptaan dalam kaitannya dengan Sang Pencipta. Demikian pula, filsafat mencoba untuk memahami dan menjelaskan segala aspek dalam realitas sejauh pengamatan manusia. Cara pendekatan dan sifat pengetahuannya berbeda, tetapi kebenaran hasil pengamatan manusia tidak akan bertentangan dengan kebenaran wahyu ilahi karena sumbernya sama. Demikian pula, Aquinas percaya bahwa segala pengetahuan manusia memiliki tujuan tertinggi (final dan ultimate end) yang sama, yaitu pengetahuan tentang the past Cause itu sendiri. Karena itu, filsafat dan semua disiplin ilmu manusia lainnya perlu dipimpin dan diarahkan oleh teologi.
Barangkali, contoh pemakaian filsafat dalam teologi dari Aquinas yang sangat terkenal adalah lima argumen (five proofs atau five ways) yang Aquinas kemukakan tentang keberadaan Allah. Ia memakai filsafat Aristoteles tentang the first mover, efficient cause, being, teleology, dan the highest good untuk membuktikan bahwa keberadaan Allah dapat dipahami oleh akal manusia. Banyak orang salah mengerti bahwa melalui lima argumen ini, Aquinas membangun teologi di atas dasar filsafat. Kalau kita membaca dengan teliti bagian dalam Summa Theologiae tersebut, kita akan mendapati bahwa Aquinas bukan bermaksud untuk membuktikan keberadaan Allah, dan kemudian di atasnya ia membangun teologi. Yang ia maksud adalah bahwa iman kita kepada Allah bukanlah sekadar "wishful thinking", melainkan dapat dimengerti atau didemonstrasikan secara sah oleh akal sehat. Artinya, Aquinas bukan mengatakan bahwa tanpa lima argumen tersebut, kita tidak dapat memercayai Allah atau bahwa lima argumen tersebut adalah landasan iman kita. Argumen-argumen tersebut adalah sebuah penegasan tentang iman kita. Aquinas hendak menegaskan bahwa iman kita kepada Allah adalah iman yang bisa diuji kebenarannya dengan akal budi manusia. Dengan iman, kita menerima kebenaran yang melampaui akal, tetapi bukan kebenaran itu bertentangan dengan akal manusia. Dalam banyak aspek kebenaran teologi, kita bahkan dapat memakai akal untuk menjelaskan atau mempertahankan iman Kristen. Contohnya adalah lima argumen tentang keberadaan Allah dari Aquinas.
Di bagian lain lagi, Aquinas memakai filsafat Aristoteles sebagai kerangka pemikiran, tetapi mengubah isinya dengan pemahaman dari Alkitab. Di bagian tentang hakikat manusia dan prinsip hidup manusia, Aquinas menerima pendapat Aristoteles tentang prinsip hidup manusia yang sifatnya teleologis, yaitu bahwa setiap perbuatan manusia memiliki makna untuk mencapai tujuan atau kesempurnaan (telos) manusia yang tertinggi yang bukan hanya berbentuk aktualisasi segala potensi (moral maupun intelektual) pada diri manusia, tetapi juga partisipasi di dalam keberadaan Allah sendiri. Kita berusaha untuk berbuat yang baik dan yang benar karena di dalam diri kita ada dorongan untuk menjadi makin lama makin serupa dengan Allah. Bahasa yang dipakai oleh Aquinas adalah bahasa Aristoteles tentang natur manusia yang bersifat teleologis, tetapi isi yang Aquinas berikan dalam kerangka pikir ini sama sekali asing dari Aristoteles. Aquinas memperkenalkan, misalnya, bahwa untuk mencapai telos tersebut, manusia membutuhkan kehadiran anugerah -- sebuah konsep yang sepenuhnya Kristen. Dengan berbuat demikian, ia mendapati bahwa filsafat adalah alat bantu yang efektif untuk menjelaskan tentang Allah dan manusia menurut pola pikir yang dapat dipahami oleh akal budi kita, tanpa mengorbankan isi iman Kristen.
Diambil dan disunting dari:
| Judul buku | : | Veritas, Jurnal Teologi dan Pelayanan |
| Judul bab | : | Mengubah Air Filsafat Menjadi Anggur Teologi |
| Judul artikel | : | Thomas Aquinas |
| Penulis | : | Kalvin S. Budiman |
| Penerbit | : | SAAT, Malang 2010 |
| Halaman | : | 175 -- 179 |
Dear e-Reformed Netters,
Bertepatan dengan hari pendidikan Nasional Indonesia pada bulan Mei, maka e-Reformed dengan sengaja mengambil artikel yang membahas tentang tantangan pendidikan Kristen di ranah formal abad 21. Mari kita simak, dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk memberi komentar tentang isi artikel ini, silakan bergabung di Facebook e-Reformed < http://fb.sabda.org/reformed >. Soli Deo Gloria.
Pemimpin Redaksi e-Reformed,
Ayub
< ayub(at)in-christ.net >
< http://reformed.sabda.org >
Tantangan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Masa Kini di Ranah Formal
Kesadaran akan kekinian zaman dalam konteks tantangan pendidikan dan pengajaran, sepatutnya secara reflektif membawa juga kesadaran dari pihak pemimpin dan pendidik Kristen akan adanya tantangan pendidikan dan pengajaran kristiani, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya dalam rangka menunaikan misi Amanat Agung Tuhan Yesus. Seperti telah dipaparkan oleh Tilaar bahwa pendidikan secara umum terkait erat dengan perubahan zaman pada era globalisasi abad ke-21 ini, demikian pula halnya dengan pendidikan Kristen.
Dikatakan oleh Michael J. Anthony dalam bukunya yang berjudul Introducing Christian Education: Foundations for the Twenty-first Century bahwa karakteristik abad ke-21 ini adalah terus meningkatnya komunikasi, pasar internasional yang pesat, ekonomi global, pasar bebas, dan relasi yang multinasional. Semua hal baru ini telah membawa dampak yang mendalam dalam kehidupan generasi sekarang. Dalam konteks Amerika, ada tiga paham filosofis multikulturalisme, naturalisme, dan relativisme yang telah menggerus sistem hukum moral dan etika bangsa Amerika dan juga sistem pendidikan di sekolah negeri. Dikatakan lebih lanjut bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Kristen pada abad ke-21 ini adalah menghadapi serangan dari semua paham filosofis humanistik sekuler pada satu sisi, dan pada sisi lain mendidik orang Kristen dengan kebenaran mutlak yang hanya terdapat di dalam Alkitab. Tantangan yang lebih luas datangnya dari kalangan masyarakat masa kini yang semakin lama semakin sekuler dalam sistem nilai dan kehidupannya.
Pada era globalisasi ini, jelaslah bahwa pengaruh filsafat humanistik telah menyebar dan berdampak pada sekolah-sekolah Kristen, bahkan perguruan tinggi Kristen. Dikatakan oleh Chadwick bahwa memang pendidikan Kristen semakin sekuler, yaitu pendidikan digambarkan sebagai kekristenan yang berlapis cokelat/chocolate-coating Christianity. Maksudnya adalah, keseluruhan praksis pendidikan di sekolah Kristen telah dibangun di atas basis filosofi pendidikan sekuler, cuma telah ditambahkan dengan program-program pendidikan Kristen, seperti: kebaktian sekolah di tengah minggu, saat teduh setiap pagi, pelajaran khusus agama Kristen, retret tahunan, dan lain-lain. Dengan demikian, program-program pendidikan Kristen ini tidak mewarnai seluruh dinamika kehidupan dan proses belajar-mengajar, baik dalam diri para murid maupun para gurunya. Sebab itu, dapat dikatakan bahwa sekolah-sekolah Kristen tersebut hampir tidak berbeda dari sekolah-sekolah umum. Lebih lanjut, Chadwick menyatakan bahwa banyak sekolah Kristen, baik di level sekolah dasar maupun sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi pun, sekadar menyandang nama Kristen saja. Pada umumnya, lembaga pendidikan Kristen ini lebih menjalankan praksis pendidikannya dengan menekankan prestasi akademis semata, keunggulan lulusan yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bergengsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kenaikan peringkat sekolah dalam persaingan lokal-nasional-internasional, fasilitas perangkat keras dan lunak yang makin lengkap dan canggih, dan lain sebagainya. Hal serupa terjadi dalam praksis pendidikan, mungkin di kebanyakan perguruan tinggi Kristen.
Sepanjang tolok ukur pendidikan Kristen berorientasi pada sukses akademis, permasalahan berikutnya yang akan muncul sebagai konsekuensi logisnya adalah terjadinya persaingan yang kurang sehat di antara lembaga pendidikan Kristen. Fenomena ini terlihat jelas dari semakin berlombanya kegiatan open house yang dijadwalkan makin awal -- baru saja dilakukan penerimaan siswa baru, beberapa bulan kemudian sudah digelar open house lagi. Pasca open house, orang tua yang berhasil mendaftarkan anaknya akan dituntut untuk segera membayar dana pembangunan, sekalipun memang ada beberapa sekolah yang memperbolehkan orang tua untuk mencicil sekian kali. Sangatlah tidak heran bila ada sebutan bahwa akhir-akhir ini, lembaga pendidikan Kristen tertentu lebih cenderung berorientasi bisnis daripada misinya.
Menjawab semua tantangan ini, sebenarnya para pemimpin gerejawi yang semula menjadi pendiri hendaknya berpartisipasi secara aktif dengan cara merumuskan ulang filosofi pendidikan kristiani. Tindakan ini benar-benar perlu diambil karena filosofi pendidikan berfungsi sebagai kemudi yang akan mengarahkan dan menentukan tujuan dan totalitas kurikulum dari proses belajar-mengajarnya. Dengan demikian, nama atau identitas "Kristen" tidak akan menjadi nama tanpa makna. Filosofi pendidikan Kristen berisi tentang pernyataan-pernyataan dari prinsip-prinsip dasar yang esensial, yang mendasari praksis pendidikan Kristen secara komprehensif di lapangan. Beberapa prinsip dasar tersebut di antaranya adalah: (1) meyakini dan menjunjung tinggi Alkitab sebagai kebenaran mutlak, karena Alkitab adalah penyataan Tuhan secara tertulis; (2) meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga pendidikan Kristen diawali dengan keselamatan/hidup baru di dalam Kristus; (3) meyakini bahwa setiap murid adalah ciptaan Allah menurut gambar dan rupa Allah, yaitu sebagai ciptaan yang sangat baik di hadapan-Nya, tetapi yang telah jatuh ke dalam dosa; (4) meyakini bahwa lulusan yang pandai/berhikmat tidaklah diukur dari kepemilikan ilmu pengetahuan natural yang tanpa pengenalan akan Kristus sebagai hikmat Allah yang sejati. Tanpa Kristus, hikmat manusia adalah kebodohan; (5) meyakini bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang hadir sebagai mitra keluarga.
Tantangan lain yang bersifat spesifik terkait dengan salah satu elemen penting dalam pendidikan dan pengajaran, yakni: kurikulum. Pada umumnya, lembaga pendidikan formal sering kali kurang atau bahkan tidak mengkritisi kurikulumnya, seakan tidak ada pihak yang mempertanyakan filosofi yang mendasarinya, padahal jelas bahwa tidak ada kurikulum yang hampa filosofi atau ideologi tertentu. Jika dikaitkan dengan elemen metodologi, fungsi kurikulum terkait erat dengan metodologi, bagaikan "sebuah panah dengan busurnya" yang dipakai seorang pemanah untuk membidik sasaran. Gambaran ini menunjukkan bahwa kurikulum adalah salah satu alat utama untuk mewujudkan tujuan akhir dalam bentuk profil peserta didik yang akan dihasilkan. Akibatnya, jika suatu lembaga pendidikan didasarkan pada filosofi pendidikan yang bersifat "sekuler", secara otomatis kurikulum pendidikannya akan berisi tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kajian empiris yang secara teologis disebut sebagai kebenaran yang natural.
Pada saat kurikulum dibangun di atas dasar falsafah pendidikan yang mengesampingkan kebenaran supranaturalisme, profil alumni yang akan dihasilkan mungkin saja menunjukkan prestasi yang unggul dan siap bersaing pada era globalisasi ini, tetapi janganlah lupa bahwa kesuksesan akademis dan keterampilan bekerja itu tidak dibarengi dengan pembaruan hati sebagai inti kehidupan seseorang. Para alumni akan berkiprah sebagai kaum profesional yang mungkin saja menjadi pelaku kejahatan berkerah putih. Mengapa demikian? Pendidikan umum tanpa transformasi spiritualitas di dalam Kristus tidak dapat menyelesaikan masalah manusia terkait kegelapan hati yang penuh dosa dan yang cenderung jahat, bahkan sejak kecilnya (Kejadian 6:5; Kejadian 8:21). Palmer mengungkapkan kondisi ini dalam pribadi orang-orang yang berpendidikan tinggi masa kini -- yaitu bahwa mereka ini berkompetensi untuk berfungsi dalam masyarakat yang bercirikan teknologi, tetapi mereka dikuasai oleh kegelapan batin yang sejak awal penciptaan menguasai diri Adam dan Hawa. Jika fakta ini terus tidak disadari, atau disadari tetapi dibiarkan oleh para pemimpin Kristen dan para tokoh pendidikan Kristen, secara langsung atau tidak langsung kita semua mendukung lembaga-lembaga pendidikan Kristen sebagai wadah pendidikan yang sedang mencetak para penjahat terdidik (educated gang).
Bersyukur bahwa ternyata Tuhan membangkitkan sekian tokoh pendidikan Kristen untuk mengatasi tantangan global dari pendidikan Kristen. Pada tahun 90-an, ada beberapa asosiasi pendidikan di Amerika yang bertekad untuk mempromosikan nilai-nilai kristiani melalui program sertifikasi para pendidik Kristen, bahkan sampai taraf akreditasi lembaganya. Salah satu di antara asosiasi ini telah berkarya dan terus mengembangkan sayapnya dalam skala internasional, yaitu: Association of Christian Schools International (ACSI). Sampai sekarang, asosiasi ini telah menjangkau sebanyak kurang lebih 150 negara di seluruh manca negara, termasuk di Indonesia. Di setiap negara, ada basis penyelenggaranya yang dipimpin oleh seorang direktur sebagai pengelola dan penyelenggara semua program pendidikannya, bahkan termasuk semua distribusi literatur pendidikan Kristen yang memuat kurikulum yang mengintegrasikan iman dan ilmu. Asosiasi ini telah memberikan kontribusi sangat berarti, khususnya dalam membangun pendidikan Kristen yang berbasis Alkitab, yang dijabarkan dalam lima elemen penting di bawah ini:
Elemen pertama adalah Kebenaran. Huruf "K" besar merujuk pada Kebenaran firman Allah sebagai kebenaran mutlak yang dinyatakan Allah dalam Alkitab untuk melawan paham relativisme. Alkitab berfungsi sebagai fondasi pendidikan Kristen. Melalui Alkitab, peserta didik belajar bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang berharga dan selayaknya juga menghargai orang lain. Melalui Alkitab juga, berita keselamatan disampaikan kepada peserta didik agar mereka mengalami lahir baru sebagai awal dimulainya pendidikan kristiani. Melalui program pemahaman Alkitab, peserta didik dibimbing untuk lebih memahami dan menaati firman Tuhan.
Elemen kedua adalah Integrasi Alkitab dalam pemahaman dan penerapan integrasi iman dan ilmu. Mengingat bahwa tidak ada kurikulum yang bebas nilai, maka upaya integrasi Alkitab dilakukan untuk mengajarkan bahwa seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah di mana pun didapatkannya -- termasuk di dalam setiap disiplin ilmu. Dengan menegakkan integrasi Alkitab, peserta didik diajarkan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah sehingga seluruh kebenaran yang diperoleh dari disiplin ilmu mana pun seharusnya merefleksikan kehadiran dan karya-Nya, dan pada akhirnya, setiap ilmuwan akan memuliakan keagungan Penciptanya. Alkitab berfungsi untuk memberikan perspektif dalam mengembangkan cara pandang kristiani. Tanpa integrasi iman dan ilmu, lembaga-lembaga pendidikan Kristen secara eksplisit sedang mempromosikan sekularisme dan naturalisme yang mengarahkan peserta didik lebih memercayai kebenaran yang bersifat ilmiah (natural) daripada kebenaran Alkitab (supranatural).
Elemen ketiga adalah staf yang seluruhnya Kristen. Staf yang dimaksud terdiri dari para guru, administrator, dan karyawan Kristen. Mereka adalah jajaran pendidik dan nonpendidik yang bukan hanya mengaku Kristen dan mengenal Kristus, melainkan juga menghadirkan gaya hidup kristiani yang akan dicontoh oleh peserta didik.
Elemen keempat adalah potensi di dalam Kristus. Sekolah Kristen sebagai lembaga pendidikan kristiani hendaknya menggali potensi setiap individu anak didik sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, maka seluruh potensi hendaknya dimaksimalkan berdasarkan sistem nilai kekal. Tujuan akhir pendidikan bukan aktualisasi diri yang berorientasi kepada diri sendiri, melainkan desentralisasi diri yang berorientasi pada sesama dan Tuhan.
Elemen kelima adalah praktik organisasional. Seluruh kegiatan operasional dan kebijakan didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran yang alkitabiah. Orang tua adalah mitra pendukung sekolah yang selalu menjalin hubungan saling membantu dengan para guru. Alangkah baiknya bila ada orang tua yang juga duduk di yayasan sekolah dalam rangka turut menjaga arah dan kualitas pendidikan yang kristiani.
Membagikan kelima elemen ini kepada semua sekolah Kristen dalam konteks Indonesia merupakan suatu perjuangan tersendiri karena tidak semua sekolah Kristen menyambut kehadirannya dan bersedia untuk dibantu dalam menyelaraskan identitas dan praksisnya. Tentu saja banyak kendala di lapangan, selain biaya, kesibukan para guru, keterbukaan pihak yayasan, dan lain sebagainya. Namun, suatu hal yang menggembirakan adalah bahwa semakin banyak sekolah telah menyadari peran penting dari ACSI, baik dalam program sertifikasi pendidik maupun sertifikasinya. Namun, barangkali tantangan yang masih perlu diatasi adalah menjangkau dan memperlengkapi para anggota yayasan sebagai perumus kebijakan makro dari sekolah dan perguruan tinggi Kristen, agar benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan Kristen yang sejati (education that is truly Christian).
Tantangan pendidikan Kristen di Indonesia masa kini di ranah formal masih cukup memprihatinkan. Sebuah gambaran faktual yang disampaikan melalui sebuah seminar Pendidikan Kristen pada 12 Desember 2011 di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, -- dengan pembicara David Yohanes Chandra (Ketua Majelis Pendidikan Kristen Indonesia) dan Jonathan L. Parapak (Rektor Universitas Pelita Harapan), bahwa sekian sekolah Kristen di Indonesia sudah ditutup. Berdasarkan sebuah ground research, dinyatakan bahwa keunikan/ciri khas pendekatan dan terapan pendidikan Kristen sudah tidak ditemukan lagi. Artinya, kekristenan sudah ditinggalkan. Lebih buruk lagi adalah bahwa di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Manado, Jawa Tengah, dan lain-lain, ada sekian sekolah sudah ditutup dan sekian sekolah secara radikal telah menghapus label/nama sekolah Kristen dan menggantinya dengan nama sekolah umum. Penyebabnya tentu saja cukup banyak, di antaranya adalah faktor biaya yang tinggi, jumlah pendaftaran siswa baru yang makin menurun, dan banyak yang "terjebak" dalam spirit pragmatisme dan sekularisme. Mengatasi problema besar seperti ini, UPH telah berinisiatif untuk melakukan take over beberapa sekolah selama periode empat belas tahun untuk pembenahan. Pada akhir periode ini, sekolah-sekolah ini akan diserahkan kembali kepada lembaga-lembaga penyelenggara semula. Inisiatif seperti ini sungguh sangat baik untuk diikuti oleh lembaga-lembaga Kristen lain atau universitas-universitas Kristen lainnya yang terbeban mengatasi tantangan sekolah-sekolah Kristen yang sedang membutuhkan bantuan.
Diambil dan disunting dari:
| Judul buku | : | STULOS Jurnal Teologi |
| Judul bab | : | Tantangan dalam Pendidikan dan Pengajaran Masa Kini |
| Penulis | : | Tan Giok Lie |
| Penerbit | : | STT Bandung, 2013 |
| Halaman | : | 9 -- 16 |